Prolog
Al-Qur'an adalah kitab suci [sacred book] terakhir yang diturunkan untuk seluruh manusia, dan dipandang sebagai petunjuk [hidayah] yang menyediakan solusi bagi berbagai problem kehidupan. Dalam rangka menggali petunjuk-petunjuk qur'anik ini para intelektual melahirkan ragam metodologi pembacaan [manhaj al-qira'ah] yang tepat, sesuai tuntutan perkembangan sosial masing-masing. Hermeneutik—sebagai salah satu metode pembacaan teks kontemporer—saat ini sedang menemukan momentumnya di hampir seluruh belahan dunia, juga di Dunia Islam, dengan sekian banyak pemikirnya.
Hassan Hanafi adalah wakil pemikir kontemporer Muslim yang dikenal cukup concern bergelut dalam perumusan isu-isu metodologis seputar hermeneutika al-Qur'an. Latar belakang sosial budaya Hanafi yang akrab dengan problem konkret seperti keterbelakangan, kemiskinan, buta huruf, penindasan hingga penjajahan multidimensi, mendorongnya untuk merumuskan sebuah metode pembacaan teks yang berpijak pada kenyataan-kenyataan aktual dan riil, yaitu hermeneutika “empiris” al-Qur'an. Bedanya dengan rumusan lain adalah bahwa hermeneutika Hanafi, di samping berangkat dari realitas “empiris” kemanusiaan, juga sampai pada perumusan taktis untuk kepentingan transformasi sosial.
Riwayat Singkat
Hanafi adalah sedikit dari tipikal pemikir muslim kontemporer yang dibesarkan dalam “dua dunia” keilmuan yang sangat berbeda: Dunia Timur yang “mistis” dan Dunia Barat yang “rasionalis”. Beliau merupakan pribadi paling beruntung yang mendapat kesempatan melakukan pengembaraan intelektual tiada henti dalam dua tradisi ilmiah sekaligus. Boleh dibilang jarang intelektual muslim yang memperoleh kesempatan “emas” seperti ini. Dari Dunia Timur, Hanafi mendapat sumbangan intelektualnya yang signifikan dalam khazanah-khazanah keilmuan klasik Islam. Wajar, sebagai seorang yang dibesarkan dalam lingkungan ke-Islam-an yang kental, beliau sangat akrab dengan warisan (tradisi) keilmuan Muslim klasik. Apalagi negeri Mesir—kota kelahiran beliau—dikenal sebagai pusat kajian dan aktivitas keilmuan Islam paling terkemuka serta tertua dalam sejarah Islam.
Sementara dari Dunia Barat Hanafi banyak mengadopsi berbagai teori dan metode ilmiah kontemporer dalam beragam disiplin keilmuan. Episteme rasionalisme dan empirisisme yang sangat berpengaruh dalam karakter hermeneutiknya merupakan sumbangan ilmiah Barat yang paling “membekas”.
Publik internasional lebih mengenal Hanafi sebagai seorang pemikir hukum Islam dan profesor filsafat terkemuka di Mesir. Dilahirkan 13 Februari 1935 di Kairo, Mesir, tepatnya di perkampungan al-Azhar dekat benteng Salahuddin. Kota ini merupakan tempat bertemunya para mahasiswa muslim di seluruh dunia yang ingin belajar, terutama di Universitas al-Azhar. Pada tahun 1956, ia memperoleh gelar Sarjana Muda Bidang Filsafat dari University Of Cairo. Sepuluh Tahun kemudian (1966), Hanafi telah mengantongi gelar Doktor dari La Sorbonne, sebuah universitas paling terkemuka di Perancis. Setelah menamatkan studinya, ia kembali ke Mesir untuk menjabat staf pengajar di almamaternya, Universitas Kairo, untuk kuliah Pemikiran Kristen Abad Pertengahan dan Filsafat Islam.
Pada tahun 1951, dia melihat dengan matanya sendiri pembantaian para Syuhada oleh tentara Inggris. Hatinya berontak, dan setelah itu dia dengan suka rela membantu gerakan revolusi yang meletus pada tahun 1952. Pada tahun yang sama pula, dia bermaksud bergabung dengan kelompok Ikhwanul Muslimin. Namun karena dalam kelompok ini terjadi kericuhan internal—terjadi perdebatan yang memanas—dia pun bergabung dengan organisasi lain yaitu organisasi Mesir Muda. Rasa kekecewaannya pun ia salurkan dengan banyak membaca buku tokoh-tokoh Islam. Dia tertarik dengan pemikiran Sayyid Qutub tentang keadilan sosial dalam Islam, pemikiran agama, revolusi dan perubahan sosial.
Kegiatan akademis selanjutnya di Sorbonne University, Paris, menjadi momen paling penting dalam membentuk karakter pemikiran Islam Hanafi di kemudian hari. Di universitas ini pula ia menyelesaikan program master dan doktoralnya pada tahun 1966, dengan disertasi yang berjudul L Exegese de la Phenomenologi, L’etat actual de la methode Phenomenologue et son Aplication au phenomeno Religiux. Sebuah karya yang berupaya memperhadapkan Ilmu Ushul Fiqih dengan Filsafat Fenomenologi Edmund Husserl. Dengan karyanya ini Hanafi mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Mesir dan dinobatkan sebagai penulis karya ilmiah terbaik di Mesir. Sekembalinya ke Mesir ia mendapatkan kepercayaan menjadi dosen mata kuliah Pemikiran Kristen Pertengahan dan filsafat Islam di Universitas Kairo.
Selain di Mesir, pada tahun 1970-1987 Hanafi aktif juga memberikan kuliah di beberapa perguruan tinggi negara lainnya, seperti Prancis, Belgia, Temple University, Philadelphia Amerika Serikat, Universits Kuwait, Universita Fez Maroko, dan menjadi guru besar tamu di Universitas Tokyo dan Persatuan Uni Emirat Arab. Gagasan paling penting yang diajukannya yang sekaligus banyak mengundang respon dari berbagai pemikir lainnya ialah tentang Kiri Islam yang dijadikan sebagai nama sebuah jurnal yang diterbitkan pada tahun 1981. Di dalam jurnal itulah Hanafi secara panjang lebar mengupas masalah Kiri Islam. Walau hanya sekali terbit, teks ini cukup memiliki arti penting bagi pengkayaan khazanah pemikiran Islam Kontemporer.
Tahap-tahap Perkembangan Pemikiran Hassan Hanafi
Sebagai seorang intelektual ‘organik’ yang gerah menghadapi kondisi obyektif masyarakatnya yang serba ‘memprihatinkan’, Hanafi terus menerus bergulat mencari formula tepat bagi perubahan yang diimpikannya. Dalam situasi inilah, beliau mengalami berbagai fase perkembangan kesadaran intelektual. Menurut Azyumardi Azra, dalam Kata Pengantarnya untuk salah satu karya utama Hanafi, al-Din wa al-Tsawrah fi Misr: 1952-1981, jilid VI (Dari Dogma Ke Revolusi), perjalanan hidup Hanafi, setidaknya, menempuh tiga rangkaian perkembangan kesadaran (consciousnes). Perkembangan dan perubahan yang dialaminya dari satu kesadaran kepada kesadaran lain sangat terkait pula dengan perubahan situasi lingkungannya yang lebih luas di Mesir. Karena itu, dalam otobiografi tersebut, Hanafi lebih banyak mengungkapkan keterlibatan dan partisipasinya dalam kehidupan nasional Mesir daripada kehidupan pribadi dan keluarganya.
Sejak masih remaja, kesadaran pertama yang tumbuh dalam diri Hassan Hanafi adalah “kesadaran nasional” (national consciousnes). Pertumbuhan kesadaran ini terkait dengan kenyataan situasi Mesir yang dalam Perang Dunia II menjadi sasaran serangan Jerman. Tetapi kesadaran nasionalnya terutama dia arahkan kepada Inggris yang menduduki Mesir sejak 1882; sejak saat ini Mesir hanya menjadi bulan-bulanan kekuatan Eropa. Semangat nasionalisme Arab semakin kuat bertumbuh dalam diri Hanafi berikutan dengan pembentukan negara Israel pada 1948, yang sejak 1928 mendapat dukungan pemerintah Inggris melalui “Deklarasi Balfour”, yang menjamin penciptaan “tanah air” bangsa Yahudi di Palestina. Karena ini pula, maka daslam kesadaran nasionalismenya Hanafi menganggap Inggris sebagai musuh bangsa Arab yang sebenarnya.
Menyimpan rasa frustrasi yang sangat pahit terhadap realitas nasionalisme Arab sekuler yang gagal menyatukan bangsa Arab, Hanafi secara alamiah bergeser kepada Islam. Melanjutkan pelajaran ke Universitas Kairo, ia kemudian memasuki organisasi al-Ikhwan al-Muslimun (IM), yang sedang menemukan momentumnya, bukan hanya karena IM berdiri paling depan melawan Israel, tetapi juga karena ia percaya bahwa organisasi ini mampu menghadapi sosialisme-komunisme yang juga semakin kuat dalam lingkaran kekuasaan Mesir. Hanafi kemudian aktif dalam demonstrasi-demonstrasi IM dan politik mahasiswa di kampus Universitas Kairo. Ia sangat tidak suka kepada orang-orang komunis yang ia anggap “sebagai telah rusak; orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar; teralienasi, dan asing; memilki kecenderungan-kecenderungan yang jauh dari kebenaran; dan tidak bermoral; mereka berada di luar kecenderungan ummah”.
Masa-masa ini sampai menjelang akhir 1950-an merupakan masa bangkitnya “kesadaran keagamaan” (religious consciousness) dalam diri Hanafi. Pemikiran, wacana intelektual dan aktivisme bertitik-tolak dari motif-motif Islam. Pada masa inilah ia mengenal secara lebih mendalam pemikiran dan wacana Islam yang berkembang di lingkungan gerakan Islam (harakah). Ia membaca dan mendalami berbagai karya tokoh-tokoh gerakan Islam seperti Hassan al-Banna, Sayyid Quthb, Abu al-A’la al-Maududi, Abu al-Hassan al-Nadwi, dan lain-lain. Dalam tulisan-tulisan mereka Hanafi menemukan semangat “kebangkitan Islam” (al-nahdlah al-Islamiyah), yang sedikit banyak mempengaruhi pandangan dunia dan misi intelektual yang ia bayangkan harus dipikulnya.
Tetapi kritisisme Hanafi sebagai mahasiswa Jurusan Filsafat, Universitas Kairo, segera membuatnya mempertanyakan isi dan metodologi pemikiran Islam harakah tersebut, yang dalam pandangannya telah kehilangan relevansinya dengan realitas zamannya. Karena itu, ia mencoba menawarkan interpretasinya sendiri atas topik-topik utama filsafat Islam dan kalam hasil pemikiran ulama abad pertengahan. Di sinilah awal upaya Hanafi menuju pembentukan suatu “metode Islam berdasarkan rasionalitas tentang baik dan buruk; dan penyatuan kebenaran, kebaikan, dan keindahan”.
Menjelang akhir dasawarsa 1950-an, Hanafi berhadapan dengan berbagai krisis baik pada tingkat nasional maupun personal. Pada tingkat nasional, terjadi krisis nasional Mesir 1956, kekacauan kehidupan intelektual, dan meningkatnya penindasan pemerintah terhadap IM. Pada level personal, ia menghadapi konflik dengan sejumlah guru besarnya, sehingga ia sempat dibawa ke sidang disipliner Universitas Kairo karena dianggap telah melecehkan mereka, sehingga ia kehilangan statusnya sebagai “mahasiswa teladan” [honors student] yang semula memungkinkannya untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri. Berhadapan dengan semua krisis ini, Hanafi semakin sering datang ke masjid, dan menghabiskan waktunya membaca al-Qur’an dan mulai merasakan intuisi-intuisi filosofis Kitab Suci ini.
Pada tahap inilah Hanafi mulai bergeser kepada tingkat kesadaran baru, yaitu “kesadaran filosofis” (philosophical consciousness). Bacaannya terhadap al-Qur’an membuatnya semakin meyakini tentang pentingnya alam kesadaran filosofis, dan sekaligus tentang keharusan untuk melanjutkan perjuangan. Pendidikan lanjutan dan dinamika intelektual yang dialaminya sejak 1956 di Paris –yang menjadi salah satu pusat terpenting wacana filosofis Barat kontemporer—memberikan kontribusi besar bagi penguatan transformasi kesadaran filosofisnya tersebut. Pada masa-masa inilah Hassan Hanafi mulai merumuskan kembali “proyek besar”-nya untuk menciptakan metodologi dan teologi baru Islam dengan pendekatan-pendekatan baru pula.
Karya-karya Intelektual Hassan Hanafi
Hassan Hanafi membuat tulisan dengan kondisi yang sedang berlangsung pada saat itu. Pada fase awal pemikiran ini, tulisan-tulisan Hassan Hanafi bersifat ilmiah murni. Baru pada akhir dasawarsa itu, ia mulai berbicara tentang keharusan Islam untuk mengembangkan wawasan kehidupan yang progresif dan berdimensi pembebasan (Taharrur, Liberation). Hal itu mengisyaratkan, bahwa fungsi pembebasan jika kita inginkan, dapat membawa masyarakat pada kebebasan dan keadilan.
Periode selanjutnya pada tahun 80-an Hassan Hanafi mulai mengarahkan pemikirannya pada upaya universalisasi Islam sebagai paradigma peradaban melalui sistematisasi proyek “Tradisi dan Modernitas”. Dalam hal ini, buku al-Turas Wa al-Tajdid yang terbit pada tahun 1980 menampilkan makna Turas wa Tajdid. Kemudian ia menulis al-Yasar al-Islami (Kiri Islam); sebuah tulisan yang berbau ideologis. Jika Kiri Islam baru merupakan pokok-pokok pikiran yang belum memberikan rincian dari program pembaruannya, maka, buku Min al-Aqidah ila Al-Tsaurah (5 jilid) yang ditulis hampir sekitar 10 tahun dan baru terbit pada tahun 1988, memuat uraian rinci tentang pembaharuan dan memuat gagasan rekonstruksi ilmu kalam (teologi Islam klasik).
Karya selanjutnya adalah Muqaddimah fi ‘Ilm al-Istighrab (1991) yang merupakan karya monumental lainnya yang sempat dirampungkan Hassan Hanafi, yang di dalamnya ia memperkenalkan Ilm al-Istigrab atau oksidentalisme. Secara ideologis, Oksidentalisme versi Hassan Hanafi diciptakan untuk menghadapi Barat yang memiliki pengaruh besar terhadap kesadaran peradaban kita. Asumsi yang dibangunnya adalah bahwa Barat memiliki batas sosio politik kulturalnya sendiri. Oleh karena itu, setiap usaha hegemonisasi kultur dan pemikiran Barat atas dunia lain, harus dibatasi. Dengan demikian, Barat harus dikembalikan pada kewajaran batas-batas kulturalnya. Melalui ilm al-istighrab (Oksidentalisme), Hassan Hanafi berupaya melakukan kajian atas Barat dalam perspektif historis-kultural Barat sendiri.
Sebagai dosen filsafat Kristen, Hanafi harus mengajar selama dua tahun pertama (1966-1967) tanpa referensi yang jelas. Demi mengatasi kesulitan pengajaran subjek ini, Hanafi memutuskan untuk menulis sebuah buku daras yang berjudul Namadzij min al-Falsafah al-Masihiyyah fi al-Ashr al-Wasith: al-Mu’allim li Aghustin, al-Imam al-Bahis ‘an al-Aql la Taslim, al-Wujud al-Mahiyah li Tuma al-Akwini (Berbagai contoh filsafat Kristen abad pertengahan: ajaran Agustine, kepercayan butuh penalaran, bukan penerimaan; bentuk dan esensi menurut Thomas Aquinas).
Hanafi baru kembali menuliskan pengantar teoretis untuk proyek peradabannya pada tahun 1980. Oleh Hanafi, al-turas wa al-tajdid dimaksudkan sebagai sebuah rancangan reformasi agama yang tidak saja berfungsi sebagai tantangan intelektual Barat, tapi juga dalam rangka rekonstruksi pemikiran keagamaan Islam pada umumnya. Hanafi merumuskan eksperimentasi al-turas wa al-tajdid berdasarkan tiga agenda yang saling berhubungan secara dialektis. Pertama, melakukan rekonstruksi tradisi Islam dengan interpretasi kritis dan kritik sejarah yang tercermin dalam agenda “apresiasi terhadap khazanah klasik” (mawfiquna min al-turas al-qadim). Kedua, menetapkan kembali batas-batas kultural Barat melalui pendekatan kritis yang mencerminkan “sikap kita terhadap peradaban Barat” (mawfiquna min al-turas al-gharb). Agenda terakhir, ketiga, upaya membangun sebuah hermeneutika al-Qur’an yang baru yang mencakup dimensi kebudayaan dari agama dalam skala global, agenda mana memposisikan Islam sebagai pondasi ideologis bagi kemanusiaan modern. Agenda ini mencerminkan “sikap kita terhadap realitas” (mawfiquna min al-waqi’).
Dalam agenda pertama, Hanafi telah menulis lima volume tebal dari buku Min al-‘Aqidah ila al-Saurah: Muhawalah li i’adah Ilm Ushul al-Din (Dari Akidah Ke Revolusi: Upaya Rekonstruksi Teologi Islam) yang merupakan reformasi teologis berdasarkan kesadaran akan hilangnya wacana manusia dan sejarah dalam teologi Islam klasik. Untuk agenda kedua, Hanafi menulis Muqaddimah fi Ilm al-Istighrab (Oksidentalisme: Sikap Kita terhadap Tradisi Barat). Buku ini dimaksudkan sebagai peletak dasar bagi kajian ilmiah atas Barat dalam rangka mempelajari perkembangan dan strukturnya dan menghilangkan dominasi Barat atas kaum muslim.
Di samping sebagai wacana tandingan untuk melawan Orientalisme yang telah lama memperlakukan Timur-Islam sebagai obyek kajian ilmiahnya, yang pada kenyataannya, tak lebih dari “strategi penjajahan berkedok tradisi ilmiah”. Namun, secara umum, karya-karya Hanafi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bagian. Pertama, karya kesarjanaan di Sorbonne; kedua, buku, kompilasi tulisan dan artikel; ketiga, karya terjemahan, saduran dan suntingan. Klasifikasi pertama berupa karya kesarjanaannya adalah tiga buah (trilogi) disertasi: Les Metodes d’Exegese, essai sur La science des Fondaments de la Comprehension, ‘ilm ushul al fiqh (1965); L’Exegese de la Phenomenologie L’etat actuel de la methode phenomenologique et son application au ph’enomene religiux (1965); dan La Phenomenologie d L’exegese: essai d’une hermeneutique axistentielle a parti du Nouvea Testanment (1966).
Klasifikasi kedua dihuni lebih dari sepuluh buku: dimulai oleh Religious Dialog and Revolution (1977); Al-Turast wa al-Tajdid (1980) yang berisikan dasar-dasar proyek pembaruan Hanafi; dan Dirasat Islamiyah (1981) yang mengulas beberapa disiplin keilmuan tradisional Islam seperti Ushul Fiqh dan Teologi Islam, serta kritik atas hilangnya wacana manusia dan sejarah di dalamnya; al-Yasar al-Islami: Kitabat fi al-Nahdhah al-Islamiyyah (1981) yang memuat manifesto “Kiri Islam” yang sangat fenomenal; Qadaya Mu’ashirah: Fi Fikrina al-Mu’ashir, dua volume (1983); Dirasat Falsafiyyah (1988); Min al-‘Aqidah ila al-Saurah, empat volume tebal yang merupakan karya monumental dan paling sistematis dari Hanafi (1988), yang berisi rekonstruksi teologi Islam tradisional dalam rangka transformasi sosial; al-Din wa al-Tsaurah fi Mishr 1956-1981, delapan jilid, memuat tulisan lepas Hanafi di berbagai media (terbit 1989); Hiwar al-Masyriq wa al-Maghrib (1990); Islam in the Modern World, dua volume tebal berbahasa Inggris (1995); Humum al-Fikr al-Wathan, dua jilid (1997); Jalaluddin al-Afghani (1997); dan Hiwar al-Ajyal (1998).
Terakhir, karya-karya awal Hanafi banyak terkait dengan klasifikasi ketiga, yakni saduran dan suntingan, mengingat kebutuhan kuliah dan memperkenalkan materi dan contoh-contoh filsafat Muslim maupun Barat secara cepat dan memuaskan. Diantaranya: Muhammad Abu Husain al-Bashri: al-Mu’tamad fi ‘ilm Ushul al-Fiqh (1964-1965), dua jilid, berisikan diskusi tentang filsafat hukum Islam; al-Hukumah al-Islamiyyah li al-Imam al-Khomeini (1979); Jihad al-Nafs aw Jihad al-Akbar li al-Imam al-Khomeini (1980) yang berisi kekaguman Hanafi pada keberhasilan revolusi Iran.
Dari wilayah filsafat Barat, Hanafi menulis sejumlah buku, antara lain: Namadzij min al-Falsafah al-Masihiyyah fi al-‘Ashr al-Wasith: al-Mu’allim li Aghustin, al-Iman al-bahis ‘an al-‘Aql la taslim, al-wujud wa al-Mahiyah li Thuma al-Akwini (1968); Spinoza Risalah fi al-Lahut wa al-Siyasah (1973); Lessing: Tarbiyyah fi al-Jins al-Basyari wa A’mal al-Ukhra (1977); Jean Paul Sartre: Ta’ali Ana Mawjud (1978).
Kritik Hanafi atas Penafsiran Klasik
Menurut Hanafi, hermeneutika klasik Islam mengalami dua krisis akut yang kemudian menyebabkan kehilangan semangat dinamis dan progresifnya. Pertama, krisis orientasi. Bagi Hanafi, sebuah aktifitas penafsiran mestilah mampu mengungkapkan kepentingan masyarakat, mencerminkan kebutuhan kaum muslimin dan mencerap isu-isu kontemporer. Sebuah penafsiran mestilah punya tujuan, orientasi atau misi, yang menurutnya, untuk kepentingan transformasi sosial umat, pembelaan terhadap kondisinya dan memperjuangkan hak-haknya. Orientasi-orientasi ini yang hilang dalam wacana hermeneutika klasik. Akibatnya, tafsir tradisional tidak otonom, melainkan terjebak pada orientasi yang lebih ‘metodologis’ dari berbagai disiplin keilmuan klasik Islam. Dalam konteks ini, penafsiran lebih banyak digunakan justifikasi bagi berbagai kepentingan. Tegasnya, hermeneutika klasik tercerabut dari kebutuhan jiwa dan kepentingan masyarakat kontemporer.
Kedua, krisis epistemologis. Bagi Hanafi, wacana klasik tak memiliki suatu teori penafsiran yang otoritatif dengan prinsip-prinsip ilmiah yang terarah pada kepentingan tertentu. Tafsir klasik hanya berfungsi sebagai penjelasan tautologis dan repetitif tentang berbagai masalah yang tak berkaitan sama sekali dengan kepentingan dan realitas nyata masyarakat. Ciri tafsir seperti ini adalah kegemarannya mengulang-ulang pendapat klasik dan sifat apologetisnya dalam memformulasikan beragam argumen. Penafsiran dulu terlalu membatasi pada asfek tekstualitas Al-Qur’an atau asfek linguistik dan sejarah turunnya Al-Qur’an. Padahal, keduanya mereduksi makna. Tafsir klasik juga membatasi pada kasus-kasus spesifik yang menjadi sebab turunnya ayat, sehingga terkesan ada ‘parsialitas’ makna dan relevansi. Padahal, semangat yang dikandung teks boleh jadi bersifat universal, tidak spesifik untuk satu komunitas atau satu sebab.
Pemikiran Hermeneutik al-Qur'an Hassan Hanafi
Meski Hanafi lebih dikenal sebagai seorang filsuf ketimbang “hermeneut”, namun tulisan-tulisannya, terutama trilogi disertasinya menunjukkan bahwa beliau termasuk tokoh yang cukup bahkan sangat intens di bidang metodologi “dialog teks”, teori pemahaman atas teks (teori hermeneutika). Berbeda dengan tokoh-tokoh penafsir lainnya, Hanafi dengan tidak tanggung-tanggung, coba membangun metodologi penafsirannya di atas sekurang-kurangnya dua pilar umum: khazanah klasik Islam dan khazanah modern Barat. Dari khazanah klasik Islam, Hanafi mengambil teori filsafat hukum Islam (ilmu-ilmu fondasi pemahaman/ilmu ushul fiqh), yang menurutnya merupakan disiplin keilmuan warisan Islam yang sangat lekat dengan realitas nyata kemanusiaan.
Sementara dari khazanah Barat, Hanafi mengambil pisau analisis Marxian mengenai teori kelas untuk membaca polarisasi struktur sosial masyarakat yang menurutnya timpang dan terkotak-kotak antara kelas miskin dengan kelas kaya, tuan-budak, bawahan-atasan, kaum elit-massa bawah, rakyat-penguasa; dialektika materialisme/dialektika sejarah untuk menguji pemaknaan teks pada realitas juga dalam menggambarkan perkembangan historis kesadaran manusia; prinsip kemajuan (progresifitas) sejarah untuk memprediksi masa depan peradaban dalam upayanya menggarap proyek ”Kebangkitan Islam”; filsafat fenomenologi untuk menganalisis berbagai fenomena sosial dan pengalaman-pengalaman hidup sebagai basis atau referensi bagi aktifitas penafsiran; serta teori hermeneutika itu sendiri sebagai metode pemahaman atas tek-teks Kitab Suci.
Konsep Teks al-Qur'an
Menurut Hanafi, teks wahyu pada mulanya sangat lekat dengan realitas nyata kemanusiaan. Teks itu sendiri lahir untuk merespon realitas. Teori klasik mengenai asbab al nuzul, menunjukkan adanya relasi yang sangat kuat antara kelahiran teks di satu sisi, dengan tuntutan kondisi obyektif masyarakat di sisi lain. Itu artinya, teks bagi Hanafi, terlahir dalam ruang dan waktu, meskipun pada kenyataannya ia merupakan firman Tuhan yang transenden. Gagasan ini membawa kita pada diskusi selanjutnya mengenai konsep teks dalam pandangan Hanafi.
1. Pengertian Teks
Dalam pengertian yang sederhana, teks didefinisikan sebagai fiksasi atau pelembagaan sebuah peristiwa wacana lisan dalam bentuk tulisan, sedangkan wacana adalah suatu aktivitas sharing [saling berbagi dan tukar menukar] pendapat dan perasaan. Dalam teori bahasa, apa yang dinamakan teks tak lebih dari himpunan huruf yang membentuk kata dan kalimat yang dirangkai dengan sistem tanda yang disepakati oleh masyarakat, sehingga ketika sebuah teks dibaca, ia bisa mengungkapkan makna yang dikandungnya. Tentang teks dan wacana, Paul Ricoeur memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya, pengertian teks sebatas bentuk tulisan masih mengandung cacat.
Kalau teks adalah rekaman dari sebuah wacana seperti transkripsi sebuah seminar, bukankah hal itu masih sebuah wacana yang diabadikan dalam format tulisan? Artinya, dalam pengertiannya yang lebih ketat, teks dikatakan sebagai teks, hanya ketika sebuah gagasan dituliskan oleh pengarangnya secara sadar dan sengaja, bukannya transkripsi dari sebuah wacana. Jika pengertian kedua diambil, maka sebuah teks pidato tidak memenuhi syarat sebagai sebuah teks, karena tujuannya untuk dibacakan di depan pendengar, di mana antara pembicara dan pendengar terjadi kontak langsung.
Bahkan, dalam sudut pandang semiologi, pengertian teks lebih luas lagi. Segala sesuatu adalah teks. Semua realitas, termasuk kita sendiri, adalah teks. Di manapun kita berada, kita dikelilingi oleh teks yang menyimpan pesan. Yang paling mencolok tentu papan iklan dan tanda-tanda penunjuk jalan. Teks dalam pengertian ini hamper identik dengan kata ayat dalam bahasa Arab-al-Qur’an, yang berarti tanda [sign]. Kehadiran sebuah tanda [signifier] selalu mengasumsikan adanya obyek yang ditandai [signified].
2. Hakikat Teks: Historisitas, Subyektifitas, Ambiguitas dan Dualitas
Menurut Hanafi, setiap teks selalu merupakan refleksi realitas sosial tertentu. Teks merupakan penulisan semangat zaman yang terungkap dalam pengalaman individu dan masyarakat pada banyak situasi. Hanya saja, “meskipun teks mula-mula berasal dalam situasi-situasi sejarah yang khusus, tetapi teks menjadi sebuah sumber nilai seluruh sejarah. Toh, teks lahir dalam sejarah, tetapi ia hidup dalam meta-sejarah, yang ia istilahkan dengan Transenden. Teks itu historis, namun transenden. Teks mulai dalam kemungkinan sejarah dan berakhir dalam kebutuhan ideasional.
Teks juga bersifat subyektif. Sebab di satu sisi, penulisan teks senantiasa tunduk pada faktor-faktor subjektif, persepsi tentang kenyataan, perspektif dalam membaca dan menentukan orientasi tertentu, dan di sisi lain, adanya kenyataan bahwa makna teks ditentukan oleh sang penafsir. Dengan berani Hanafi menyebut “teks sebagai praktik ideologi”. Dalam konteks ini, teks bersifat arbitrer, karena merupakan pilihan penulisnya pada satu maksud dari keragaman fenomena yang ia hadapi untuk sesuatu di masa datang. Teks juga, bagi Hanafi, bersifat ambigu; artinya, selalu tersedia pluralitas makna, yang berasal dari pluralitas pilihan-pilihan makna yang diproduksi sang penafsir. Sebab, menurut Hanafi, teks itu sendiri kosong makna. Teks hanya akan bermakna setelah penafsir memberinya makna.
Proposisi ini membawa kita pada asumsi vitalitas dan dinamitas teks dalam pemikiran Hanafi. Dinamitas ini berpijak pada hipotesis bahwa teks pada dasarnya bersifat statis dan diam. Membaca teks berarti menghidupkannya. Teks adalah forma yang perlu diberi substansi melalui penafsiran manusia. Maka, dalam konteks penafsiran inilah, setiap teks berarti mengandung potensi dinamis yang memungkinkan dilakukannya penafsiran kreatif.
Hanafi juga berpendapat bahwa teks bersifat ganda. Prinsip amfibologis menunjukkan adanya dualitas itu, seperti prinsip pembenaran dan perhitungan, eksoterik (dzahir) dan esoterik (bathin), univocal dan equivocal, kejelasan (muhkam) dan ketidak jelasan (mutasyabih), khusus (khas/muqayyad) dan umum (‘am/muthlaq). Di sini, tugas/peran interpreter adalah menghasilkan teks pada satu bagian sisinya. Bagi Hanafi, dualitas teks merupakan refleksi dari dualitas struktur sosial dalam setiap masyarakat; kaya-miskin, penindas-tertindas, penguasa-pemberontak, minoritas-mayoritas, kaum elit-kaum masyarakat, pengatur-yang diatur. Di sini, peran interpreter adalah mengubah status quo, yaitu dominasi pihak pertama pada pihak kedua, dan menghasilkan perebutan kekuasaan antara dua belah pihak dalam membantu pihak kedua melawan pihak pertama, untuk kemenangan perubahan sosial sebagai sebuah revolusi perdamaian dan bertahap.
3. Teks: Tidak Memiliki Makna dalam Dirinya
Dalam filsafat bahasa, dikenal tiga macam teori makna, yaitu ideational, referential, dan behavioral. Teori ideational berpandangan bahwa sebuah ungkapan kalimat tidak memiliki kebenaran pada dirinya, karena kebenaran dan makna yang esensial berada secara otonom dalam bentuk ide. Teori ini berasal dari Plato. Realitas sejati dan sempurna, menurut Plato, berada di alam ide, sementara obyek dan realitas yang tertangkap oleh indra hanyalah penampakkan dan serpihan particular dari realitas yang ada di alam ide, yang tidak mungkin terjangkau secara utuh oleh indera dan penalaran manusia.
Mirip dengan teori ideational, meski dengan beberapa perbedaan, adalah apa yang disebut dengan intentional theory. Teori ini berpandangan bahwa kebenaran sebuah kalimat ataupun ungkapan bukannya terletak pada struktur kalimatnya, melainkan pada kehendak, maksud, atau intensi dari sang pembicara. Dengan demikian, yang paling tahu makna dari sebuah ungkapan adalah pembicaranya sendiri.
Teori kedua, referential theory, ada juga yang menyebutnya picture theory ini menyatakan bahwa kebenaran makna dari sebuah ungkapan dan pernyataan terletak pada ketepatan relasi antara proposisi dan obyek yang ditunjuk. Dengan dukungan kekuatan penalaran logis, teori referensial sangat dominant dalam alam pikiran modern dan metodologi ilmu pengetahuan alam yang bersifat positivistik. Sebuah statemen dan proposisi ilmiah dinyatakan valid jika mampu bertahan ketika diklarifikasi dan diverifikasi dengan mengacu pada realitas obyektif yang berada di luar kita.
Teori ketiga, behavioral berpandangan bahwa makna paling mendasar dari sebuah ungkapan terletak pada pesan yang dikehendaki oleh pembicara dalam rangka mempengaruhi perilaku pendengar atau pembicara. Teori ini sangat disadari oleh kalangan politisi dan ideolog, sehingga keluar dari mereka bahasa-bahasa jargon dan propaganda, juga digemari kalangan pebisnis modern yang sangat mengandalkan kekuatan bahasa iklan untuk mempengaruhi calon konsumen. Pada umat beragama, fenomena ini muncul dalam bentuk bahasa-bahasa dakwah yang memberi penekanan pada kekuatan retorika. Di atas berbagai pandangan tersebut, Hanafi adalah termasuk yang tidak percaya bahwa sebuah kalimat, ungkapan atau teks memiliki makna dalam dirinya. Baginya, kebenaran makna sebuah teks tergantung dari motivasi sang penafsir teks itu sendiri. Teks hanya akan bermakna atau berarti jika penafsir memberinya arti atau makna.
Teks itu sendiri kosong; hampa arti. Teks perlu disusun kembali seperti kesadaran yang kosong. Teks adalah isi yang di masa lampau perlu tanda sebuah pengeluaran arti dan pengalaman hidup pada saat ini. Teks yang dihasilkan di masa lampau, dalam sebuah visi retrospektif, dimasukkan isi dari masa sekarang, dalam visi prospektif. Kesimpulannya, teks itu sendiri formal. Teks memerlukan isi material yang datang dari pengalaman hidup di masa lampau hingga kini. Teks memerlukan sebuah jalan dari formal menuju Transendental, seperti yang dilakukan Husserl untuk logika. Dalam konteks ini, aktifitas hermeneutis tidak lain merupakan upaya pemberian isi material (pemaknaan) terhadap eksistensi teks yang “hampa makna”.
Karakteristik Penafsiran Hassan Hanafi
Menurut Hanafi, penafsiran tematik amat cocok untuk melengkapi kekurangan metode klasik. Sebab, metode ini berusaha menghindari penafsiran yang bertele-tele, sekaligus mengarahkan perhatian pada tafsir tema-tema sosial al Qur’an. Karena itulah, penafsiran Hanafi atas teks memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:
Hermeneutika al-Qur’an, pertama, harus mampu menghasilkan tafsir yang sifatnya spesifik (al-tafsir al-juz’i). Artinya, ia menafsirkan ayat-ayat tertentu al-Qur’an dan bukannya menafsirkan keseluruhan teks. Tafsir demikian mengarahkan perhatian pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam al-Qur’an dan bukan menafsirkannya secara keseluruhan. Jika yang dibutuhkan adalah pembebasan bangsa dari kolonialisme, maka penafsiran dilakukan terhadap ayat-ayat perang, jihad, dan sebagainya, ketimbang terhadap ayat-ayat lain. Kedua, tafsir semacam ini disebut juga tafsir tematik (al-tafsir al-mawdu’i), mengingat tidak menafsirkan al-Qur’an berdasarkan sistematika konkordasinya (al-tafsir al-thul), tetapi lebih senang menafsirkan keseluruhan ayat al-Qur’an dalam tema-tema tertentu.
Ketiga, hermeneutika al-Qur’an Hanafi bersifat temporal (al-tafsir az-zamani). Sebagai penafsiran yang berorientasi sosial, hermeneutika tidak diarahkan kepada proses pencarian makna universal, tetapi diarahkan untuk memberi gambaran tertentu dari keinginan al-Qur’an bagi suatu generasi tertentu. Tafsir semacam ini tidak berurusan dengan masa lalu atau masa datang, tapi dikaitkan dengan realitas kontemporer di mana ia muncul. Keempat, hermeneutika Al-Qur’an Hanafi juga berkarakter realistik (al-tafsir al-waqi’i). Yakni, memulai penafsiran dari realitas kaum muslimin, kehidupan dengan segala problematikanya, krisis dan kesengsaraan mereka dan bukan tafsir yang tercabut dari masyarakat.
Kelima, hermeneutika al-Qur’an Hanafi berorientasi pada makna tertentu dan bukan merupakan perbincangan retorik tentang huruf dan kata. Hal ini karena wahyu pada dasarnya memiliki tujuan, orientasi, dan kepentingan, yakni kepentingan masyarakat dan hal-hal yang menurut akal bersifat manusiawi, rasional, dan natural. Keenam, tafsir eksperimental. Dengan kata lain, ia adalah tafsir yang sesuai dengan kehidupan dan pengalaman hidup penafsir. Sebuah penafsiran tidak mungkin terwujud tanpa memperoleh pendasarannya pada pengalaman mufassir yang bersifat eksistensial.
Ketujuh, perhatian pada problem kontemporer. Bagi Hanafi, seorang mufassir tidak dapat memulai penafsirannya tanpa didahului oleh perhatian atau penelitian akan masalah-masalah kehidupan. Terakhir (kedelapan), posisi sosial penafsir. Posisi seseorang dalam kapasitasnya sebagai mufassir ditentukan secara sosial sekaligus menentukan corak penafsiran yang dilakukannya. Penafsiran adalah bagian dari struktur sosial, apakah penafsir merupakan bagian golongan atas, menengah atau bawah.
Asumsi Metodologis Hermeneutika al-Qur'an Hassan Hanafi
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa hermeneutika bagi Hanafi merupakan perbincangan teoretik yang mendahului peristiwa penafsiran. Berkaitan dengan itu, Hanafi terlebih dahulu mengemukakan beberapa prinsip metodologis yang berguna dalam mengarahkan kegiatan interpretasi al-Qur’an. Prinsip atau premis tersebut bagi Hanafi bukan sekadar preposisi (asumsi), tetapi juga merupakan fakta nyata, pernyataan realitas, ungkapan keadaan, pengenalan batas-batas, afirmasi pluralitas, dan motivasi dalam pencarian makna. Dengan kata lain premis-premis tersebut adalah landasan etik dan filosofis dari metode penafsiran tematik atas al-Qur’an.
Premis-premis hermeneutika al-Qur’an Hanafi dapat digambarkan sebagai berikut: Pertama, wahyu diletakkan dalam “tanda kurung” (apoche), tidak diafirmasi, tidak pula ditolak. Penafsir tidak perlu lagi mengajukan pertanyaan yang luas diperdebatkan oleh para Orientalis abad ke-19 mengenai keaslian al-Qur’an: apakah ia dari Tuhan ataukah hanya pandangan Muhammad. Penafsiran tematis mulai dari teks apa adanya tanpa mempertanyakan sebelumnya mengenai keasliannya. Ia berkaitan dengan pertanyaan tentang “apa” dan bukan “bagaimana”. Jika asal-usul historis al-Qur’an dapat diuji melalui kritik sejarah, asal-usul keilahiannya tidak dapat ditelusuri karena keterbatasan penelitian sejarah. Lagi pula, dalam tahap interpretasi, pertanyaan tentang asal-usul teks tidak lagi relevan. Teks adalah teks, tidak masalah apakah ia ilahiah atau human, sakral atau profane, religius atau sekular. Pertanyaan tentang asal-usul merupakan permasalahan kejadian teks, sementara penafsiran tematik berkaitan dengan isinya.
Kedua, al-Qur’an diterima sebagaimana layaknya teks-teks lain, seperti materi penafsiran, kode hukum, karya sastra, teks filosofis, dokumen sejarah, dan sebagainya. Artinya, ia tidak memiliki kedudukan istimewa secara metodologis. Semua teks, sakral atau profan, termasuk al-Qur’an ditafsirkan berdasarkan aturan-aturan yang sama. Pemisahan antara teks suci dan profan hanya ada dalam praktik keagamaan dan bukan bagian dari hermeneutika umum (general hermeneutics). Apalagi al-Qur’an, seperti halnya hadits Nabi, merupakan transfigurasi bahasa manusia: ia mencakup bahasa Arab dan non-Arab; berisikan ucapan orang beriman maupun orang kafir.
Ketiga, tidak ada penafsiran palsu atau benar, pemahaman benar atau salah. Yang ada hanyalah perbedaan pendekatan terhadap teks yang ditentukan oleh perbedaan kepentingan dan motivasi. Oleh karena itu, konflik interpretasi mencerminkan pertentangan kepentingan, bahkan dalam interpretasi al-Qur’an, yang bersifat linguistik sekalipun, sebab bahasa pun berubah. Akurasi penjelasan atas teks menurut prinsip-prinsip kebahasaan bahkan lebih tautologis lagi. Kesamaan antara makna teks yang sedang dijelaskan dengan makna dalam penafsiran terhadap teks hanyalah preposisi formal yang sifatnya hipotetis berdasarkan pada hukum keserupaan (Law of identity). Kesenjangan waktu lebih dari 14 abad menyebabkan teori keserupaan makna dalam teks dan penafsiran menjadi mustahil.
Keempat, tidak ada penafsiran tunggal terhadap teks, yang ada pluralitas penafsiran yang disebabkan oleh perbedaan pemahaman para penafsir. Teks hanyalah alat kepentingan, bahkan ambisi manusia. Teks hanyalah bentuk, penafsirlah yang memberinya isi sesuai ruang dan waktu dalam masa mereka.
Terakhir, kelima, konflik penafsiran merefleksikan konflik sosio-politik dan bukan konflik teoretis. Jadi, teori sebenarnya hanyalah kedok epistemologis. Setiap penafsiran mengungkapkan komitmen sosio-politik penafsir. Penafsiran adalah senjata ideologis yang digunakan banyak kekuatan sosio-politik, baik dalam rangka mempertahankan kekuasaan atau merubahnya. Penafsiran konservatif menciptakan status quo, sementara penafsiran revolusioner untuk mengubahnya.
Wallahu A’lam...
skip to main |
skip to sidebar
Belajar berkarya dan berbagi seputar Bloging, Agama, Musik, software, Seni Dll.
Top
Copyright 2009 Alex-JoeN™ All rights reserved. Powered by Blogger

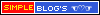


0 komentar:
Posting Komentar
Terimakasih atas kunjungannya jangan lupa komentar nya gan, Salam Silaturahmi :